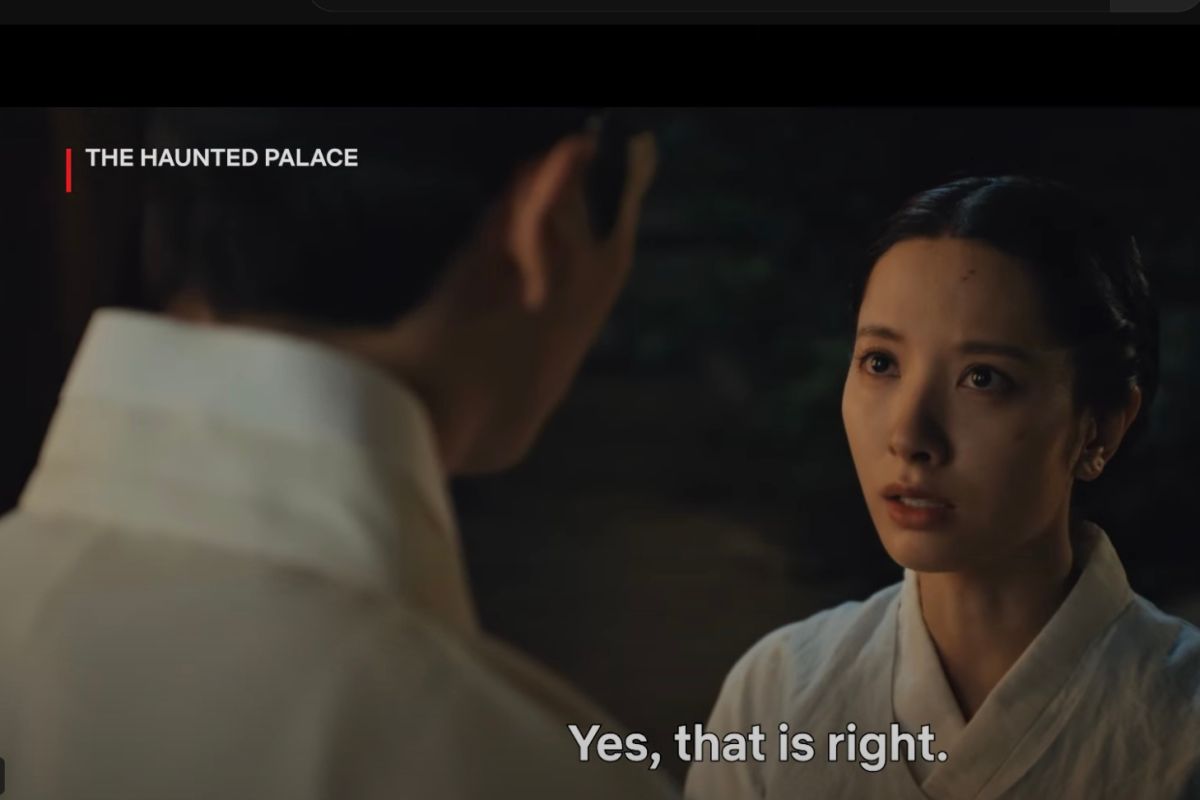Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan yang kontroversial: pengenaan pajak hiburan sebesar 10 persen atas berbagai aktivitas olahraga komersial.
Kebijakan ini dirinci secara eksplisit dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025, yang mencantumkan 21 jenis olahraga, termasuk padel, yoga, hingga sewa lapangan futsal, sebagai objek pajak hiburan.
Di tengah semangat warga kota dalam mengadopsi gaya hidup sehat, langkah ini justru menimbulkan paradoks kebijakan: olahraga, yang sejatinya vital bagi kesehatan masyarakat, diposisikan sejajar dengan aktivitas hiburan seperti tontonan bioskop dan pergelaran musik.
Aktivitas fisik teratur terbukti menjadi salah satu elemen paling efektif dalam mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas. Namun, mendorong aktivitas fisik bukan sekadar soal imbauan atau kampanye.
Riset Nola M. Ries (2012) berjudul Legal and Policy Measures to Promote Healthy Behaviour: Using Incentives and Disincentives to Control Obesity menunjukkan bahwa ruang fisik yang memadai dan lingkungan yang mendukung berperan penting dalam meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan fisik. Keberadaan taman kota, jalur pejalan kaki, serta fasilitas olahraga merupakan penunjang utama gaya hidup sehat.
Di kota-kota besar seperti Jakarta, di mana keterbatasan ruang terbuka masih cukup menantang, fasilitas olahraga komersial sering kali menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat untuk tetap aktif. Namun kini, dengan adanya pajak hiburan atas fasilitas olahraga tersebut, biaya akses meningkat.
Seseorang yang hendak mengikuti kelas yoga atau menyewa lapangan bulu tangkis harus membayar lebih mahal karena beban pajak tersebut. Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini berpotensi menghambat akses untuk mempertahankan gaya hidup sehat terutama bagi kelompok menengah ke bawah.
Disinsentif bagi gaya hidup sehat
Pajak memiliki daya pengaruh yang luar biasa terhadap perilaku. Ketika pemerintah mengenakan pajak atas konsumsi, secara tidak langsung itu menjadi sinyal terkait preferensi kebijakan pemerintah, yakni apa yang hendak dibatasi, dan apa yang ingin didorong.
Combs dan Elledge (1979) ketika membahas pajak akomodasi (yang bahkan bukan hiburan) mengingatkan pentingnya prinsip ability-to-pay dalam kebijakan pajak konsumsi. Dalam hal ini, pajak semestinya tidak membebani secara tidak proporsional kelompok berpenghasilan rendah.
Pajak atas olahraga justru bisa menjadi regresif, yakni mereka yang paling membutuhkan fasilitas olahraga akan paling terdampak oleh kenaikan biaya. Padahal, boleh jadi mereka adalah kelompok berpenghasilan rendah.
Karenanya, 21 jenis olahraga yang dikenai pajak hiburan oleh Pemprov DKI layak untuk dievaluasi. Tidak semua jenis aktivitas tersebut bersifat hiburan murni atau mewah.
Kegiatan seperti yoga, bulu tangkis, futsal, atau atletik jelas merupakan aktivitas partisipatif yang mendukung kebugaran dan sering kali dijalankan secara rutin oleh masyarakat sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
Sebaliknya, beberapa aktivitas memang layak masuk kategori hiburan atau eksklusif. Misalnya, jetski, bowling, biliar, ice skating, serta tenis atau lapangan tembak yang umumnya hanya diakses kelompok tertentu dengan daya beli lebih tinggi.
Peninjauan selektif ini penting. Bukan berarti olahraga tidak mengandung aspek hiburan, tetapi ketika aspek partisipatif dan fungsi kesehatannya lebih dominan, perlakuan fiskalnya seharusnya berbeda.
Lagipula, jika pemerintah sungguh ingin mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor ini, ada ruang untuk mendesain kebijakan yang lebih progresif, misalnya dengan mengenakan tarif lebih tinggi pada olahraga eksklusif dan membebaskan atau menurunkan tarif untuk olahraga publik atau komunitas.
Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Jumat (4/7), ketika menanggapi ramainya pemberitaan terkait pajak atas 21 objek olahraga menyebut bahwa daerah lain juga mengenakan pajak atas aktivitas olahraga. Pernyataan ini memang tidak sepenuhnya keliru, namun perlu dicermati konteks dan skalanya.
Kota Yogyakarta, misalnya, hanya menetapkan delapan jenis aktivitas dalam Perda Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2023, termasuk biliar, bowling, dan pusat kebugaran, tanpa merinci secara agresif seperti DKI Jakarta.
Target penerimaan dari pajak hiburan olahraga di Yogyakarta pada APBD 2023 pun tergolong sangat kecil dibanding jenis pajak lain, yakni hanya sebesar Rp10.000.000 untuk Pajak Pertandingan Olahraga dan Rp34.000.000 untuk Pajak Biliar dan Bowling.
Pendekatan serupa juga dilakukan oleh Kota Bandung melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang tidak merinci objek olahraga secara terperinci seperti Jakarta. Dengan demikian, tidak fair jika kebijakan DKI yang sangat rinci dan luas pembebanannya disamakan begitu saja dengan daerah lain.
Keseimbangan fiskal dan kesehatan
Bila kita terjebak pada logika bahwa setiap layanan komersial layak dikenai pajak tanpa melihat fungsi sosialnya, maka akan ada banyak kebijakan yang secara tidak langsung justru merusak tujuan pembangunan itu sendiri. Seharusnya, untuk jenis olahraga yang fungsinya jelas dalam menjaga kesehatan dan bisa diakses masyarakat luas, pemerintah bisa menerapkan pendekatan insentif fiskal.
Dalam risetnya, Ries (2012) bahkan menyebutkan bahwa beberapa yurisdiksi di Kanada dan AS telah mencoba skema kredit pajak atau subsidi bagi aktivitas fisik, dengan tujuan mendorong partisipasi lebih luas.
Memang, skema semacam itu memiliki tantangan tersendiri, seperti efektivitas dan kompleksitas administratif. Namun, semangatnya penting untuk dipahami, bahwa negara hadir bukan hanya untuk menarik pajak, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi warganya.
Salah satu opsi yang bisa dikembangkan adalah penyediaan fasilitas olahraga publik dengan skema retribusi yang akses atau tiketnya akan cukup terjangkau. Bahkan, pendapatan dari retribusi ini bisa menjadi alternatif sumber penerimaan daerah, yang mana itu lebih berkeadilan dan tetap mendukung tujuan kesehatan publik.
Di sisi lain, kebijakan fiskal daerah juga tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari ketentuan pusat. Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) memang mencantumkan secara eksplisit bahwa jasa olahraga permainan adalah objek PBJT hiburan.
Namun, semestinya kebijakan pelaksanaan di daerah tidak dilakukan secara over-generalisasi. Pemerintah daerah tetap memiliki ruang diskresi dalam merumuskan peraturan turunannya agar tidak kontraproduktif terhadap agenda kesehatan.
Pajak pada akhirnya bukan sekadar instrumen penerimaan, melainkan juga signalling terkait nilai. Di tengah krisis kesehatan masyarakat akibat rendahnya tingkat aktivitas fisik penduduk kota, kebijakan fiskal harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru sumber masalah. Jika pemerintah ingin menggenjot penerimaan, masih banyak sektor hiburan murni yang lebih layak untuk digarap.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun daerah lainnya perlu meninjau ulang kebijakan terkait pajak olahraga secara proporsional, dengan memetakan secara cermat mana saja jenis olahraga yang benar-benar layak dikenai pajak hiburan. Tanpa itu, semangat hidup sehat akan kandas di hadapan beban fiskal yang tidak proporsional. Pajak boleh bersandar pada asas konsumsi, tapi ia juga harus tunduk pada logika keadilan sosial.
*) Ismail Khozen adalah Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Manajer Riset Pratama Institute
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.