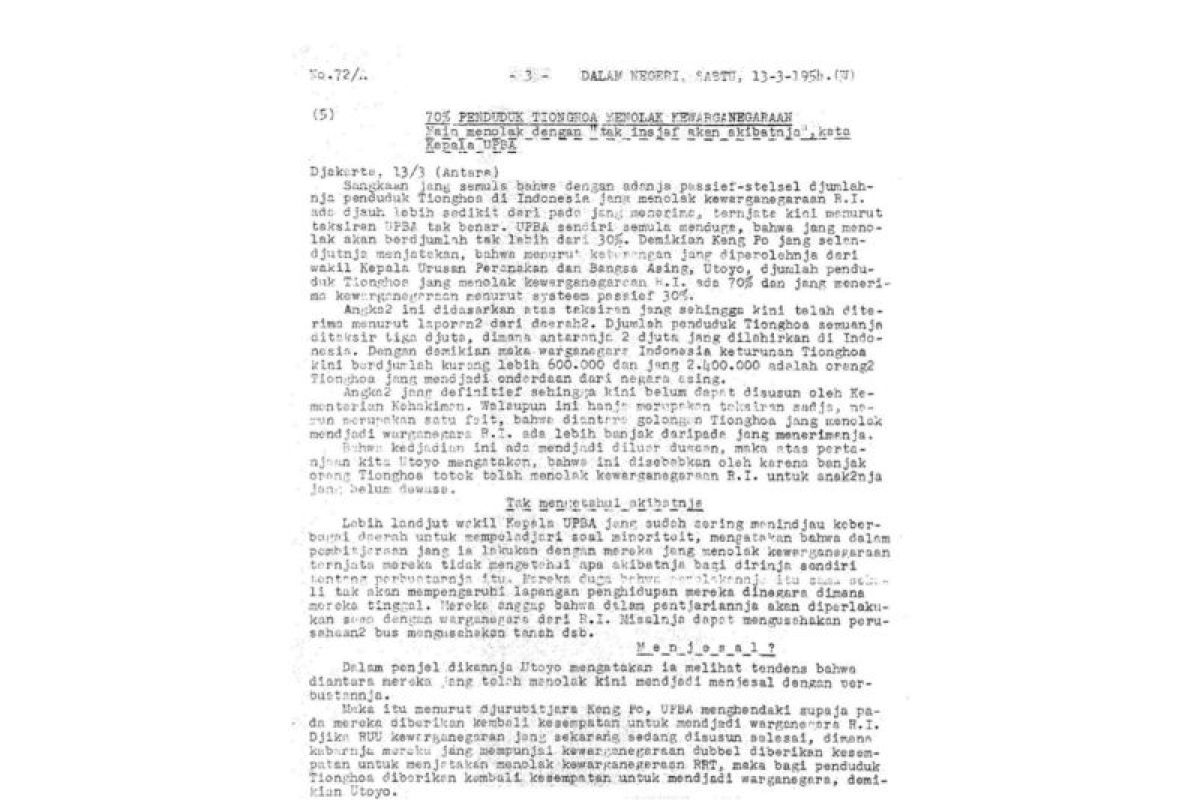Samarinda (ANTARA) - Tak akan ada habisnya jikalau hidup dibatasi pada pagar etnis yang memenjarakan kehidupan bersosial. Betapa kelam situasi bila menuruti ego etnosentris sebagaimana digambarkan secara mencekam dalam film garapan Joko Anwar "Pengepungan di Bukit Duri."
Seperti itulah kecamuk pikiran saat menyusuri Jalan Yos Sudarso, Samarinda, Kalimantan Timur, tepat di depan pelabuhan terbesar Kota Tepian. Kemudian langkah kaki ini menyusuri trotoar berbelok perlahan menuju kawasan Citra Niaga.
Di sini, memori kota seolah diputar ulang. Wali Kota Samarinda Andi Harun, belakangan sering mewacanakan revitalisasi kawasan ini menjadi Little Chinatown. Jauh sebelum Citra Niaga berdiri dengan segala riuh perniagaan, kawasan ini adalah denyut Pecinan Samarinda.
Di sudut lain, tak jauh dari sana, aroma hio menyeruak lembut, menembus udara kota. Kelenteng Thien Le Khong berdiri tegak. Warna merah dan emasnya yang mencolok bukan simbol dominasi, melainkan napas harmoni.
Itu adalah sebuah monumen hidup yang merekam bagaimana etnis Tionghoa dan penduduk lokal, yang mayoritas Banjar, Kutai, dan Bugis, hidup berdampingan tanpa sekat curiga selama berabad-abad.
Di Samarinda, kelenteng tidak perlu bersembunyi di gang sempit. Ia berdiri kokoh di pusat keramaian pada jalan protokol, menjadi bagian integral dari lanskap kota yang majemuk.
“Ketika membahas perihal Tionghoa di Indonesia, ingatan publik nyaris selalu tertuju pada sejarah isu rasialisme,” ujar Muhammad Sarip, sejarawan Kalimantan Timur, membuka percakapan. Pewarta ANTARA menemuinya untuk menggali lebih dalam tentang lapisan sosiologis yang membentuk karakter toleran di Benua Etam.
Sarip menuturkan bahwa sejarah, setragis apa pun peristiwanya, tidak bisa dihapus dalam catatan dan memori kolektif publik.
“Meskipun begitu,” lanjutnya, “memelihara ingatan sejarah memang penting. Tujuannya bukan untuk larut dalam meratapi masa lalu, tapi sebagai sarana introspeksi bagi semua elemen bangsa untuk tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama.”
Sebagaimana digambarkan dalam film "Pengepungan di Bukit Duri", ingatan bangsa ini memang punya luka menganga bernama Mei 1998. Di Jakarta, Solo, dan kota-kota besar di Jawa, etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Toko dijarah, bangunan dibakar, dan martabat manusia direndahkan dalam kekerasan seksual yang memilukan.
Bersyukur, di Kalimantan Timur, itu tak terjadi. Sarip lantas menunjukkan sebuah anomali yang menyejukkan dalam harmoni daerah yang bermajemuk. “Di Samarinda dan kota lainnya di Kalimantan Timur, saat itu warga Tionghoa dengan segala propertinya relatif aman. Tidak tersentuh aksi destruktif,” kata dia.
Fakta sejarah mencatat, di Kaltim pada Mei 1998, tidak ada penjarahan massal. Tidak ada asap hitam membubung dari toko milik Tionghoa. Dan yang paling krusial, tidak ada dugaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa di Samarinda maupun Balikpapan, dua kota metropolis Benua Etam.
“Sejarah panjang relasi penduduk di Samarinda lintas etnis berlangsung dalam suasana yang toleran dan kooperatif,” kata Sarip. Potensi konflik tentu ada, sebagaimana lumrahnya interaksi manusia, namun isu kompetitif di Kaltim tidak pernah berpretensi menjadi chaos berbasis rasial.
Dari Lo A Po
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.