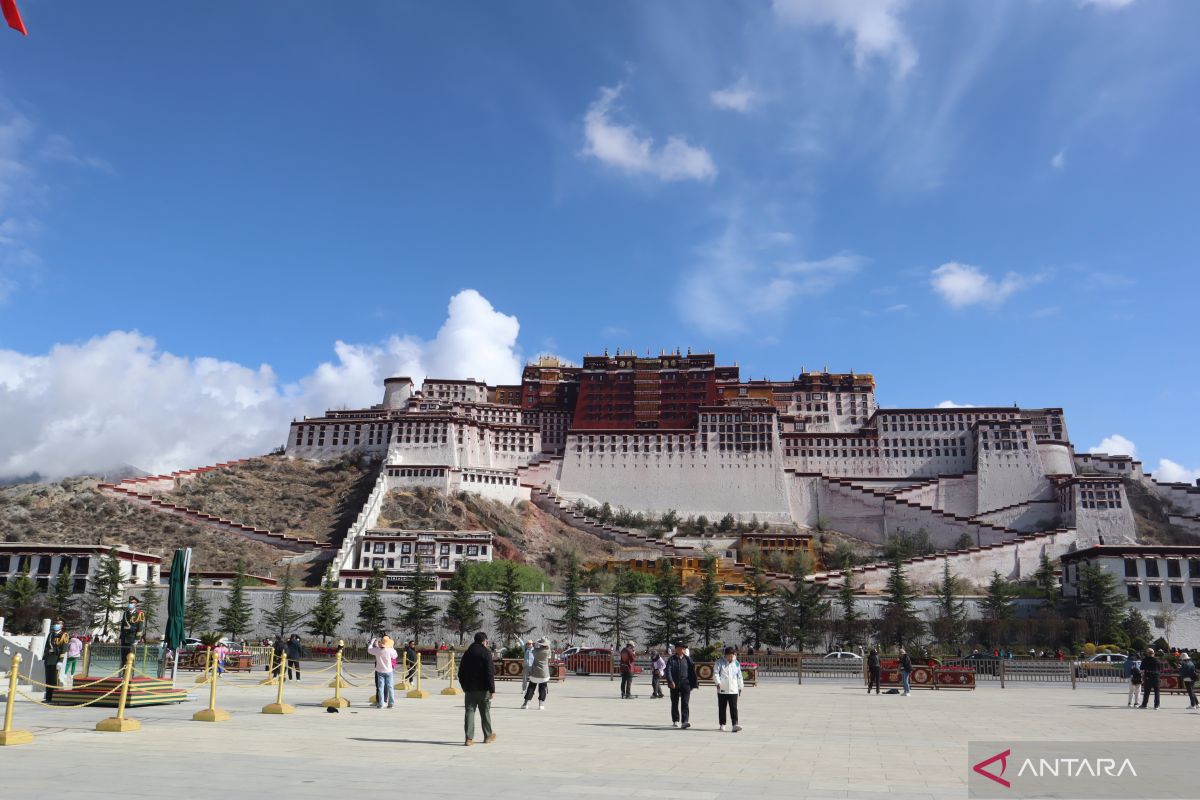Jakarta (ANTARA) - Dua puluh tahun pilkada langsung berjalan, tetapi kesejahteraan daerah tetap sangat ditentukan oleh pusat. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun ruang fiskal dan kewenangan kebijakannya justru makin menyempit.
Inilah paradoks demokrasi lokal Indonesia. Legitimasi politik diperluas, tetapi kapasitas ekonomi tidak pernah benar-benar didesentralisasikan.
Polemik mekanisme pilkada kembali mengemuka, ditandai dengan menguatnya usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan ini memperoleh dukungan mayoritas partai politik parlemen dengan argumen klasik yang nyaris tak berubah sejak satu dekade lalu.
Pilkada langsung dianggap mahal, rawan korupsi, melelahkan, dan memicu konflik. Komposisi aktor pendukung perubahan ini pun menunjukkan kemiripan mencolok dengan situasi pada 2014.
Ironisnya, di tengah dorongan mengakhiri pilkada langsung, hampir tidak terlihat upaya serius untuk memperbaiki dampak negatifnya. Pengetatan aturan pembiayaan politik, penegakan hukum terhadap politik uang, atau kebijakan untuk menurunkan biaya kontestasi elektoral, jarang menjadi agenda utama.
Padahal, jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, kualitas demokrasi lokal justru berpotensi meningkat tanpa memangkas hak pilih warga.
Selama ini, pilkada langsung kerap diposisikan sebagai tonggak demokrasi lokal yang diyakini mampu mendorong kesejahteraan. Logikanya sederhana. Pemimpin yang dipilih langsung akan lebih akuntabel, lebih responsif, dan pada akhirnya lebih efektif memperbaiki layanan publik.
Namun setelah hampir dua dekade, klaim ini tidak pernah terbukti secara konsisten. Kepercayaan politik memang meningkat di sejumlah daerah, tetapi dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi warga jauh dari seragam. Bahkan kerap mengecewakan.
Di sinilah problem mendasarnya. Demokrasi terlalu sering dinilai dari prosedur pemilihan, bukan dari kapasitas institusi yang menopang hasil pilihan tersebut. Pilkada langsung menjadi pusat perdebatan, sementara struktur fiskal, desain kewenangan, dan relasi kekuasaan lokal dibiarkan nyaris tak berubah. Demokrasi akhirnya berhenti sebagai ritual elektoral, bukan sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan.
Baca juga: Yusril: Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.